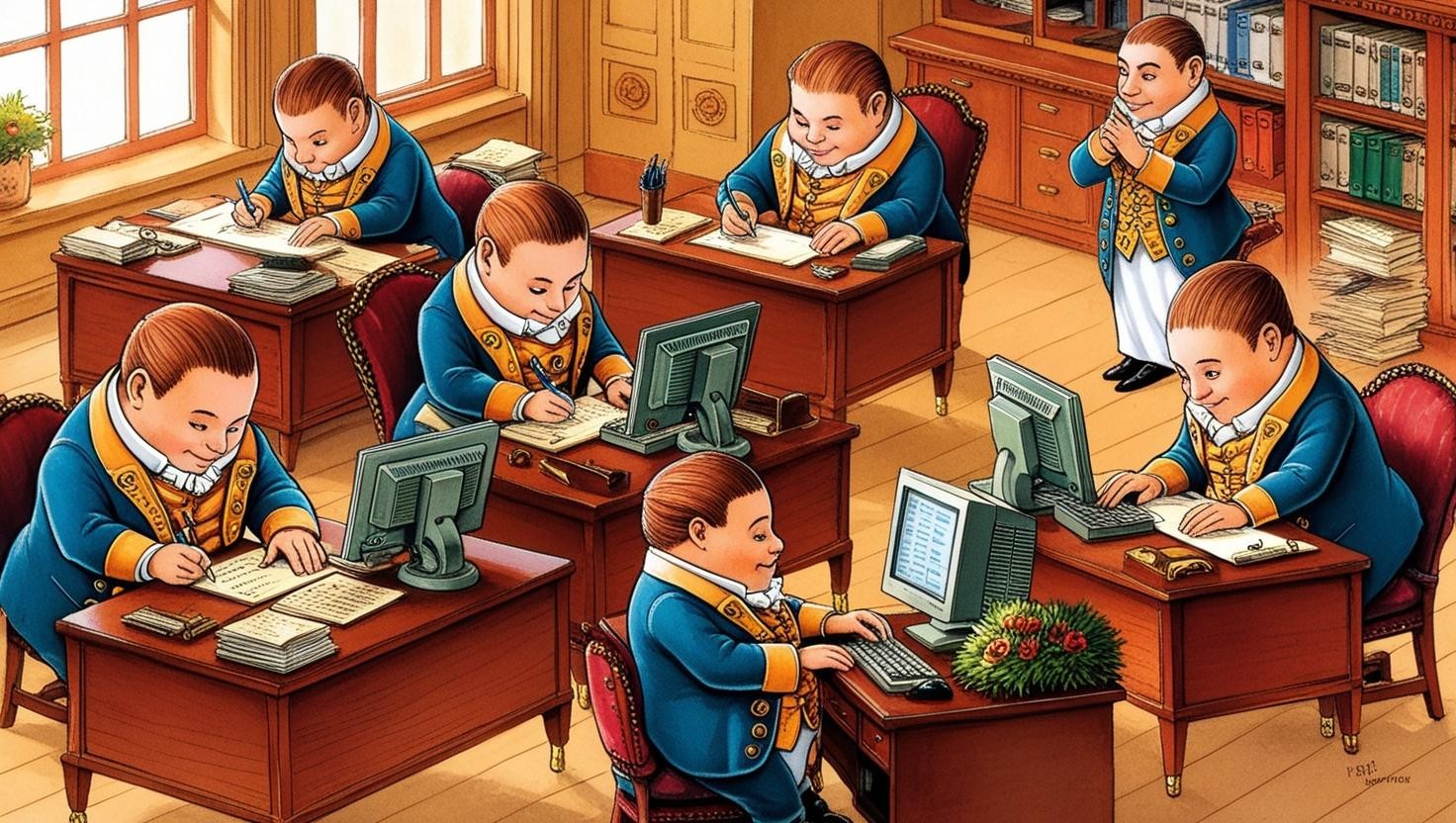Yang Tersisa Dari Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2025
Saatnya Berhenti Bangga, Mulailah Bertindak Nyata
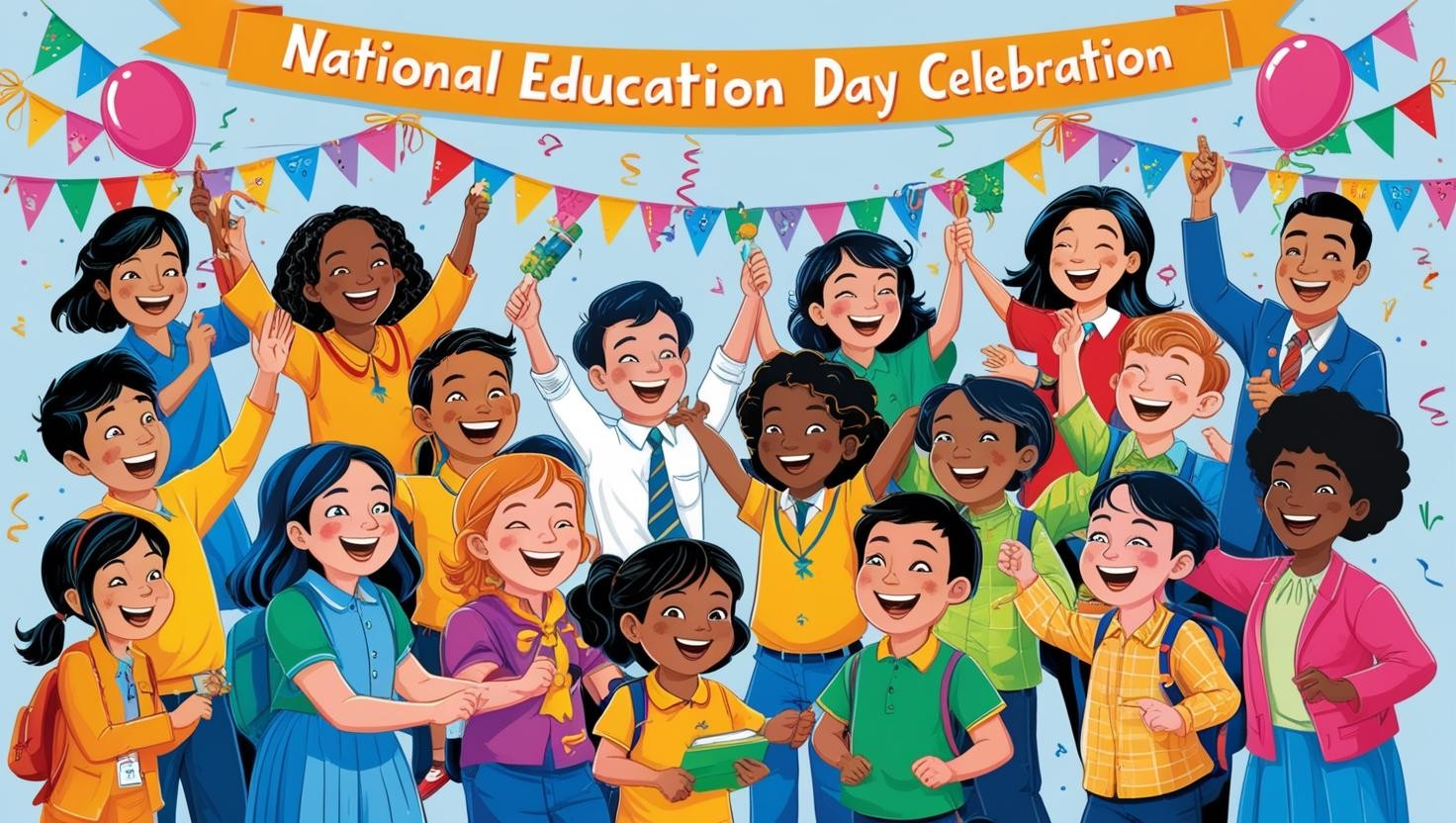
Gambar : ilustrasi
Setiap tanggal 2 Mei, kita rutin merayakan Hari Pendidikan Nasional dengan gegap gempita. Seremonial diadakan di berbagai daerah, pidato mengalun dengan penuh semangat, dan media sosial penuh dengan kutipan-kutipan Ki Hajar Dewantara. Namun usai upacara selesai dan bendera dilipat, kita kembali pada kenyataan: pendidikan Indonesia masih tertinggal jauh, baik dalam capaian maupun keberpihakan.
Sudah terlalu lama kita bangga secara semu pada angka partisipasi pendidikan yang meningkat, pada keberadaan platform digital, atau pada prestasi individual yang jarang terjadi namun diangkat sedemikian rupa sebagai bukti keberhasilan sistem. Padahal, fakta global dan nasional bicara sebaliknya.
PISA dan PIAAC: Dua Cermin Realitas Pendidikan dan Keterampilan Indonesia
Dalam upaya memahami kualitas pendidikan dan kompetensi masyarakat Indonesia, dua instrumen global dari OECD perlu dipahami secara mendalam: PISA dan PIAAC. Keduanya sering dikutip dalam laporan pendidikan, namun memiliki cakupan dan tujuan yang sangat berbeda dan keduanya sama pentingnya untuk mengukur arah kemajuan bangsa.
PISA (Programme for International Student Assessment) adalah penilaian terhadap siswa usia 15 tahun, sebuah titik kritis ketika mereka diharapkan telah memiliki kemampuan literasi, matematika, dan sains yang memadai untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi atau memasuki dunia nyata. Indonesia secara konsisten berada di peringkat bawah, dengan sebagian besar siswa kesulitan menyelesaikan soal-soal dasar yang menguji pemahaman dan nalar kritis.
Sementara itu, PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) mengukur kemampuan orang dewasa usia 16 hingga 65 tahun dalam aspek yang sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari: literasi, numerasi, dan pemecahan masalah di lingkungan digital. Hasilnya pun menunjukkan bahwa banyak orang dewasa Indonesia tidak memiliki keterampilan dasar yang dibutuhkan di dunia kerja modern.
Jika PISA menunjukkan seberapa baik/buruk hasil dari sistem pendidikan formal, maka PIAAC mengungkap akumulasi keberhasilan/kegagalan sistem tersebut dalam jangka panjang. Kita tidak hanya sedang berbicara tentang siswa yang tertinggal, tetapi tentang generasi dewasa yang tidak dibekali dengan keterampilan esensial untuk berkontribusi secara produktif dalam ekonomi digital dan masyarakat berbasis informasi.
Dua survei ini adalah alarm keras. Pendidikan tidak boleh berhenti pada pencapaian di sekolah, tetapi harus menjadi investasi jangka panjang yang terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.
Maka itu, kebijakan pendidikan dan pelatihan vokasional di Indonesia perlu disusun tidak hanya berdasarkan kurikulum ideal, tetapi juga berdasarkan kenyataan yang ditunjukkan oleh data PISA dan PIAAC.
Dalam hasil asesmen internasional PISA (Programme for International Student Assessment) tahun 2022, skor Indonesia menunjukkan stagnasi yang mengkhawatirkan. Dari 81 negara, Indonesia berada di peringkat bawah dalam literasi membaca, matematika, dan sains. Sekitar 70% siswa tidak mampu menyelesaikan soal level dasar, yang sejatinya menjadi fondasi bagi pembelajaran selanjutnya.
Tak jauh berbeda, hasil survei PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) yang diinisiasi OECD menggambarkan kondisi literasi dan numerasi orang dewasa Indonesia masih rendah. Ini bukan sekadar masalah generasi muda, tapi juga masalah kompetensi lintas generasi.
Ini semua mengindikasikan bahwa sistem pendidikan kita belum mampu membekali generasi dengan kemampuan berpikir kritis, bernalar, dan memecahkan masalah secara fungsional. Di tengah dunia yang bergerak cepat dan menuntut adaptasi tinggi, ketertinggalan ini adalah ancaman besar bagi masa depan bangsa.
Waktunya Berhenti Berpuas Diri
Selama ini, narasi yang dibangun sering kali terlalu optimistis tanpa disertai kedalaman refleksi. Kita terjebak dalam self-congratulatory narratives bangga pada capaian-capaian kecil namun enggan melihat lubang besar yang menganga di sistem pendidikan kita. Ketika skor PISA rendah, kita berkata “masih dalam masa transisi.” Ketika hasil literasi digital buruk, kita berdalih “koneksi belum merata.”
Padahal, waktu tidak menunggu. Negara lain terus bergerak cepat memperbaiki sistem, mengubah paradigma belajar, membangun budaya kualitas, dan menyiapkan guru-guru terbaik sejak awal. Kita justru masih sibuk menyusun regulasi, mengganti kurikulum, dan berpolemik soal seragam dan P5.
Langkah Prioritas yang Harus Dilakukan
1. Perkuat Kompetensi Guru dan Kepala Sekolah
Guru bukan pelengkap sistem mereka adalah sistem itu sendiri. Bangun program pelatihan yang nyata, berkelanjutan, dan berbasis praktik. Libatkan guru dalam komunitas belajar yang kolaboratif. Berikan kepala sekolah peran sebagai pemimpin pembelajaran, bukan sekadar birokrat pelapor dana BOS.
2. Bangun Ekosistem Literasi Sejak Dini
Literasi bukan sekadar kemampuan membaca teks, tapi membaca dunia. Perlu ada kebijakan yang mendorong pengembangan literasi sejak dini, pembiasaan membaca di rumah, hingga penguatan pustaka sekolah yang hidup.
3. Evaluasi Kurikulum dan Asesmen dengan Serius
Kurikulum apapun tidak akan berhasil tanpa asesmen formatif yang bermakna. Guru harus diberdayakan agar mampu memetakan capaian belajar siswa, bukan hanya menilai angka.
4. Fokus pada Ketimpangan dan Keadilan Akses
Wilayah 3T, anak-anak dari keluarga miskin, disabilitas, dan perempuan masih menghadapi kesenjangan besar dalam mengakses pendidikan berkualitas. Program afirmasi harus ditingkatkan, bukan hanya dalam bentuk kuota, tetapi pendampingan nyata dan sumber daya yang memadai.
Momentum untuk Bertindak, Bukan Sekadar Berharap
Pendidikan bukan proyek lima tahunan. Pendidikan adalah kerja lintas generasi yang hanya berhasil jika semua pihak bersinergi dan benar-benar paham arah perubahannya. Ini bukan tugas Kemendikbud Ristek semata, melainkan kewajiban kolektif: pemerintah daerah, guru, orang tua, dunia usaha, dan masyarakat luas.
Hari Pendidikan Nasional tahun ini seharusnya tidak hanya menjadi perayaan nostalgia terhadap ajaran Ki Hajar Dewantara, tetapi juga panggilan refleksi keras:
Apakah kita hanya ingin terus mengulang kata-kata indah dalam upacara, atau benar-benar ingin mewujudkan pendidikan yang memerdekakan dan memampukan anak bangsa?
Guru dan Kepala Sekolah Ujung Tombak Reformasi Pendidikan Indonesia
Dalam setiap diskusi tentang kemajuan pendidikan, kita kerap terjebak pada wacana kurikulum, teknologi, atau anggaran. Padahal, satu hal yang sering terlupakan namun memiliki dampak paling besar adalah kualitas sumber daya manusianya terutama guru dan kepala sekolah. Tanpa guru yang cakap, tidak ada kurikulum yang bisa dijalankan dengan baik. Tanpa kepala sekolah yang visioner, tidak ada lingkungan belajar yang sehat dan transformatif yang dapat tumbuh di sekolah.
Perayaan Hari Pendidikan Nasional menjadi momentum tepat untuk merefleksikan bahwa investasi terbesar dalam pendidikan bukan pada infrastruktur fisik, melainkan pada kompetensi dan karakter pendidik itu sendiri. Sayangnya, berbagai studi nasional dan internasional menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam hal ini.
Realitas Saat Ini, Tantangan yang Tidak Bisa Diabaikan
Beberapa tahun terakhir, hasil asesmen pendidikan seperti PISA dan ANBK telah menunjukkan bahwa banyak siswa Indonesia kesulitan memahami bacaan, gagal menyelesaikan persoalan matematika sederhana, atau tidak mampu menarik kesimpulan dari data sains dasar. Namun sebelum kita menyalahkan anak-anak, mari kita bertanya: apakah para guru telah benar-benar dipersiapkan untuk mengajar di era yang kompleks ini?
Banyak guru yang masih mengajar dengan pendekatan lama, minim refleksi, dan tidak terbiasa menggunakan asesmen formatif selama proses pembelajaran untuk memahami kebutuhan siswanya. Tidak sedikit pula kepala sekolah yang lebih sibuk menyelesaikan laporan administratif daripada membina kualitas pengajaran di sekolahnya.
Sementara itu, pelatihan guru sering kali bersifat formalitas berbasis ceramah, bukan praktik. Guru hadir, menandatangani daftar, dan kembali ke kelas tanpa membawa keterampilan baru yang benar-benar terinternalisasi.
Mengapa Kompetensi Guru dan Kepala Sekolah Begitu Vital?
Guru adalah aktor utama di ruang kelas. Mereka yang menghadapi siswa setiap hari, bukan menteri atau pejabat pendidikan. Jika seorang guru tidak memahami cara membangun literasi siswa, atau tidak mampu menjelaskan konsep matematika dasar dengan sederhana, maka seluruh tujuan kurikulum akan gagal di eksekusi.
Di sisi lain, kepala sekolah adalah pemimpin yang menentukan arah gerak sekolah. Mereka bukan sekadar manajer administratif, melainkan instructional leaders yang seharusnya menginspirasi guru untuk terus belajar, mendorong inovasi pengajaran, dan menciptakan kultur sekolah yang mendukung pertumbuhan murid secara menyeluruh.
Solusi Strategis untuk Peningkatan Kompetensi yang Terstruktur dan Bertahap
Untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara sistemik, peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah harus menjadi prioritas utama dalam agenda pendidikan nasional. Beberapa langkah yang dapat dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan antara lain:
1. Reformasi Rekrutmen dan Sertifikasi Guru
-
Seleksi calon guru harus berbasis kompetensi mengajar yang terukur, bukan sekadar administrasi.
-
Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) harus diperkuat dan dimodernisasi agar mencetak guru masa depan yang paham pedagogi, literasi digital, dan psikologi belajar anak.
-
Sertifikasi guru perlu dirombak menjadi proses berkelanjutan yang mengevaluasi praktik mengajar secara langsung, bukan hanya portofolio.
2. Pelatihan Berbasis Kebutuhan dan Kontekstual
-
Pelatihan harus dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata di kelas, bukan materi generik.
-
Program seperti “Guru Belajar dan Berbagi” dapat diperluas dan difokuskan pada praktik kelas, asesmen formatif, dan literasi numerasi.
-
Pelatihan yang efektif bukan yang dilakukan satu kali, melainkan yang diikuti dengan praktik, umpan balik, dan pembinaan berkelanjutan.
3. Pemberdayaan Kepala Sekolah sebagai Pemimpin Pembelajaran
-
Kepala sekolah harus dibekali pelatihan instructional leadership agar mampu membina guru dan mengarahkan strategi peningkatan mutu belajar.
-
Beban administrasi kepala sekolah perlu dikurangi dengan digitalisasi manajemen, sehingga mereka bisa fokus pada pembinaan mutu.
-
Kepala sekolah seharusnya dinilai dari kualitas pembelajaran di sekolahnya, bukan sekadar kelengkapan dokumen atau penggunaan anggaran.
4. Penguatan Komunitas Belajar dan Kolaborasi
-
Setiap sekolah harus menjadi pusat pembelajaran guru, bukan sekadar tempat kerja.
-
Komunitas belajar guru (KBG atau MGMP) perlu difasilitasi dan difungsikan sebagai wadah refleksi, eksperimen, dan inovasi pengajaran.
-
Pengawas/Pendamping sekolah juga harus dibekali kompetensi menjadi mentor, fasilitator, trainer,coach, bukan hanya auditor.
Guru Sebagai Pahlawan Perubahan
Bangsa ini tidak akan pernah melangkah maju jika kita terus menaruh guru dan kepala sekolah hanya sebagai pelaksana kebijakan. Mereka harus diangkat sebagai pemimpin pembelajaran, diberikan ruang untuk tumbuh, dan dihargai bukan hanya secara simbolis, tetapi secara profesional.
Seorang guru yang menginspirasi akan meninggalkan jejak sepanjang hayat pada muridnya. Seorang kepala sekolah yang memimpin dengan visi akan membentuk ekosistem belajar yang sehat untuk seluruh warga sekolah.
Maka, jika kita benar-benar ingin pendidikan menjadi jalan menuju kemajuan bangsa dan bukan sekadar tema pidato. investasi paling strategis yang bisa kita lakukan hari ini adalah: meningkatkan kompetensi guru dan kepala sekolah. (Irene)

.gif)